views

Peringatan Hari Ibu di Indonesia setiap tahunnya kerap terasa kurang nyambung. Sebab banyak orang yang tidak mengetahui sejarah tercetusnya Hari Ibu tersebut. Penetapan tanggal Hari pada 22 Desember mengacu pada pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta pada 22-25 Desember 1928. Atau beberapa pekan setelah pelaksanaan Kongres Sumpah Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda.
Kongres Perempuan Indonesia I yang berlangsung pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda itu diikuti oleh tidak kurang dari 600 perempuan dari puluhan perhimpunan wanita yang terlibat tanpa memandang latar belakang sosial dan budaya. Spirit gerakan para perempuan menjadi signifikan mengingat masa itu Indonesia masih berada dalam kendali kolonial yang mana kebebasan berpendapat adalah hal yang nyaris tidak mungkin ada. kehadiran semangat itu juga tak bisa lepas dari peristiwa Sumpah Pemuda.
Faktor yang mendorong adanya Kongres adalah kehidupan perempuan yang masih terkungkung dalam budaya patriarkis yang berdiri di atas nilai-nilai feodalisme. Perempuan tak memiliki kebebasan berpendapat dan tak bisa mengenyam ilmu seperti halnya laki-laki pada zaman itu. Dalam buku Saskia Eleonora Wieringa, aktor kunci pelaksanaan Kongres Perempuan ini adalah tiga tokoh perempuan yang berusaha untuk "mengatasi provinsialisme dalam gerakan wanita". Ketiganya adalah Ni Hajar Dewantara/Ibu Suwardi (tokoh pendidik), Ni Suyatin (Pemimpin Putri Indonesia, organisasi perempuan guru-guru sekolah yang didirikan pada 1926), dan Ny. Sukonto (Anggota Wanito Utomo dan guru di HIS).
Beberapa organisasi perempuan yang terpenting ikut dalam Kongres Perempuan yang ikut serta antara lain Wanito Utomo, Aisyiyah, Poetri Indonesia, Wanita Katholik, Wanito Mulyo dan bagian-bagian perempuan di dalam SI, Jong Islamieten Bond, Jong Java, Jong Madoera dan Taman Siswa. Selain itu, para perwakilan dari perhimpunan pergerakan, partai politik, maupun organisasi pemuda juga datang ke Kongres Perempuan perdana ini, termasuk wakil dari Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia (PNI) dan seterusnya.
Dinukil dari buku karya Blackburn, R.A. Sukonto mengatakan “Zaman sekarang adalah zaman kemajuan. Oleh karena itu, zaman ini sudah waktunya mengangkat derajat kaum perempuan agar kita tidak terpaksa duduk di dapur saja. Kecuali harus menjadi nomor satu di dapur, kita juga harus turut memikirkan pandangan kaum laki-laki sebab sudah menjadi keyakinan kita bahwa laki-laki dan perempuan mesti berjalan bersama-sama dalam kehidupan umum.”
Ada banyak masalah yang dibicarakan dalam kongres perempuan pertama itu, mulai dari pendidikan kaum perempuan, nasib anak yatim piatu dan janda, perkawinan anak-anak, reformasi undang-undang perkawinan Islam, pentingnya meningkatkan harga diri kaum perempuan sampai dengan kejahatan kawin paksa yang masih marak terjadi saat itu. Beberapa tokoh perempuan menyampaikan pandangannya masing-masing terhadap persoalan yang dihadapi kaum perempuan di Indonesia, bahkan muncul gerakan anti-permaduan (baca: anti-poligami). Kongres Perempuan Indonesia pertama itu menghasilkan sejumlah resolusi dan membentuk Perikatan Perkumpulan Perempoean Indonesia.
Kehidupan kaum perempuan di Hindia Belanda pada era tahun 1920-an dirundung oleh sejumlah masalah yang cukup pelik. Tak banyak perempuan yang bisa menempuh pendidikan; kebanyakan dari mereka sudah dikawinkan selang beberapa saat setelah mengalami menstruasi pertama; tak punya kedudukan kuat untuk menggugat atas perlakuan sepihak dari kaum pria dalam soal kawin-cerai dan tak adanya aturan yang berpihak kepada mereka.
Dalam surat-suratnya kepada Ny. Abendanon bisa diketahui bagaimana RA. Kartini menggugat praktik permaduan yang terjadi di kalangan priayi. Ironisnya, Kartini yang menggugat praktik permaduan dan perjodohan paksa itu pada akhirnya harus takluk kepada kehendak ayahnya yang menjodohkannya dengan K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, bupati Rembang yang sudah beristri tiga. Surat-surat Kartini merupakan gambaran alam pikiran dan perasaannya yang diserap dari pengalaman dan kesaksiannya sebagai seorang perempuan Jawa-priayi yang hidup dalam kungkungan budaya patriarkis. Semangat Kartini itulah yang terus dinyalakan oleh kaum perempuan yang hidup sesudahnya, termasuk oleh mereka yang menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia pertama, 22 Desember 1928.
Gerakan perempuan Indonesia pada kolonial sempat hampir pecah karena adanya perbedaan pandangan mengenai permaduan. Itu terjadi pada Kongres Perempuan Indonesia kedua, 20–24 Juli 1935 di Batavia, ketika Ratna Sari, dari Persatuan Muslim Indonesia (Permi) Sumatera Barat menyampaikan pidato yang bernada mendukung poligami, sesuai dengan syariat Islam. Kontan sikap Ratna itu menuai kontroversi. Suwarni Pringgodigdo dari perkumpulan Istri Sedar menentang pendapat Ratna. Suwarni bahkan memboikot jalannya sidang dengan menyatakan dirinya dan organisasi yang dipimpinnya keluar dari kongres. Namun hal itu akhirnya dapat dicegah setelah Maria Ulfah, tokoh perempuan utama lainnya, mengajukan usul agar pembahasan pendapat Ratna tidak diteruskan di dalam kongres.
Dinamika gerakan perempuan makin menguat seiring makin bersatunya orientasi mereka terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan. Perempuan tak lagi berdiam di dapur atau pasrah menerima nasib yang terjadi pada diri mereka. Sejumlah advokasi terhadap perempuan korban pertikaian rumah tangga dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan anggota kongres perempuan. Perempuan Indonesia, sejak 22 Desember 1928 memasuki ranah perjuangan politik praktis, sebuah wilayah yang sebelumnya tabu mereka masuki karena nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat yang tak memungkinkan mereka bergerak aktif memperjuangkan hak-haknya.
Peringatan hari Ibu 22 Desember kemudian ditetapkan perayaannya secara nasional melalui Dekrit Presiden Sukarno No. 316 tahun 1959. Banyak yang mengatakan bahwa penetapan tersebut merupakan upaya dari Sukarno untuk memperbaiki citranya di hadapan gerakan perempuan karena dia telah memadu Fatmawati dengan menikahi Hartini. Namun lebih dari itu, hari Ibu di Indonesia merupakan tonggak sejarah perjuangan kaum perempuan untuk merebut posisi yang lebih adil di dalam masyarakat. Maka, peringatan hari Ibu yang penuh haru-biru dengan segala puja-puji peran domestik ibu di dalam rumah sejatinya justru mendistorsi makna hari Ibu itu sendiri. Saatnya momen Hari Ibu dijadikan spirit perjuangan perempuan untuk terus melawan budaya patriarki yang tidak adil gender.













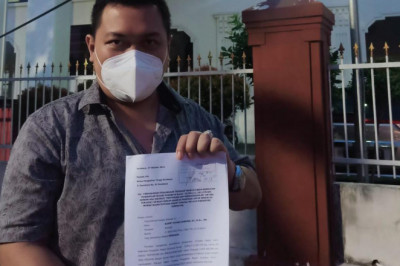






Facebook Conversations